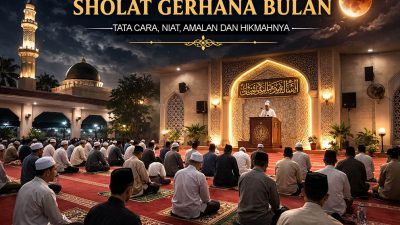Jombang, pcnujombang.or.id – Bayangkan seorang siswa SD di Jombang yang bangun pukul 5 pagi setiap hari Senin hingga Jumat, tiba di sekolah pukul 6.45, dan baru pulang pukul 15.30.
Setelah seharian di kelas, ia masih harus menyelesaikan tumpukan PR, meninggalkan sedikit waktu untuk bermain dengan saudara atau membantu orang tua di rumah.
Cerita ini bukan fiksi; survei dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menunjukkan bahwa kebijakan sekolah lima hari dengan sistem full day sering menyebabkan siswa mengalami kelelahan mental, penurunan konsentrasi, dan kurang tidur karena jadwal yang padat.
Seorang guru di Yogyakarta, misalnya, melaporkan bahwa murid-muridnya menjadi lebih pendiam dan kurang antusias setelah berbulan-bulan menjalani rutinitas ini, sementara ia sendiri merasa burnout karena harus mengelola kelas yang lebih lama tanpa dukungan memadai.
Pengalaman serupa dialami ribuan siswa di berbagai daerah Indonesia sejak kebijakan ini digulirkan melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2023. Di sekolah-sekolah pedesaan, anak-anak yang biasanya membantu orang tua di sawah atau ikut kegiatan madrasah diniyah sore hari kini kehilangan kesempatan itu.
Sebuah studi dari UIN Walisongo menemukan bahwa siswa full day school cenderung lebih dekat dengan teman sekolah daripada keluarga, tapi ini justru menimbulkan isolasi emosional—mereka jarang berinteraksi dengan tetangga atau kakek-nenek, yang selama ini menjadi sumber pembelajaran nilai-nilai adat dan moral.
Dampaknya? Perilaku belajar berubah: siswa lebih pasif di kelas karena kelelahan, dan motivasi belajar menurun, seperti yang dilaporkan dalam riset tentang stres akademik di sekolah full day.
Tidak hanya siswa, guru juga terdampak. Di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, guru-guru yang menerapkan full day melaporkan gangguan keseimbangan kerja-rumah tangga; mereka pulang larut, melewatkan momen bersama anak sendiri, dan merasa bersalah.
Riset dari International Journal of Advanced Education menemukan bahwa guru menjadi lebih kreatif dalam mengajar untuk menghindari kebosanan siswa, tapi ini datang dengan harga: peningkatan stres dan penurunan kepuasan kerja.
Di sisi positif, beberapa sekolah melaporkan peningkatan skor mata pelajaran tertentu berkat waktu ekstra untuk diskusi dan ekstrakurikuler, seperti klub bahasa Inggris yang meningkatkan kemampuan siswa secara kognitif.
Meluas ke konteks nasional, kebijakan ini mengancam lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan madrasah diniyah, yang telah menjadi tulang punggung pembentukan karakter bangsa.
Di Jawa Tengah, misalnya, banyak anak yang sebelumnya belajar Al-Qur’an di sore hari kini absen karena kelelahan setelah sekolah formal.
Nahdlatul Ulama (NU) secara tegas menolak kebijakan ini dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama 2023, menyebutnya sebagai “interpretasi liar” yang mengabaikan kesejahteraan mental siswa dan guru.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengkritik, mencatat bahwa interaksi anak-orang tua berkurang drastis, berpotensi melahirkan generasi yang rapuh secara sosial.
Data dari penelitian di sekolah dasar menunjukkan bahwa siswa full day lebih rentan terhadap perilaku konsumtif selama libur akhir pekan, seperti berlama-lama dengan gadget, alih-alih terlibat dalam aktivitas komunitas atau keagamaan.
Jika kita tarik perspektif lebih luas ke tingkat internasional, pola serupa terlihat di negara-negara yang menerapkan extended school hours atau full day models.
Di Amerika Serikat, program extended learning time di sekolah-sekolah urban seperti di Massachusetts menunjukkan peningkatan pencapaian akademik dan pengurangan repetisi kelas, mirip dengan temuan dari reformasi tahun sekolah lebih panjang di Indonesia pada 1978-1979, yang meningkatkan tingkat pendidikan, employability, dan upah di kemudian hari.
Namun, riset dari OECD tentang extended days di Eropa dan Amerika Latin mengungkap sisi gelap: siswa mengalami kelelahan fisik dan mental, dengan peningkatan risiko anxiety dan depresi, terutama jika program tidak didukung fasilitas rekreasi yang baik.
Di Cina, boarding schools—yang mirip full day dalam hal durasi harian—dikaitkan dengan gejala depresi lebih tinggi di kalangan siswa pedesaan, karena kurangnya dukungan emosional dari keluarga.
Dari segi psikologis, studi global menunjukkan bahwa anak-anak dengan jadwal sekolah panjang cenderung mengalami penurunan kesejahteraan emosional.
Penelitian di Australia membandingkan boarders (siswa asrama) dengan day students, menemukan bahwa meski boarders punya rasa tujuan hidup lebih tinggi, mereka lebih rentan terhadap masalah psikologis seperti kesepian dan kesulitan mengekspresikan emosi.
Di Abu Dhabi, hubungan antara sekolah dan rumah memengaruhi kebahagiaan anak; extended hours yang mengurangi waktu keluarga dapat memperburuk ini.
Bahkan, meta-analisis tentang day care ekstensif di usia dini menunjukkan efek negatif jangka panjang pada perilaku sosial-emosional, seperti peningkatan agresi atau hiperaktivitas.
Secara kultural, extended hours sering bentrok dengan sistem pendidikan tradisional. Di negara-negara seperti Brasil atau Portugal, perpanjangan jam sekolah memengaruhi partisipasi dalam kegiatan budaya lokal, mirip dengan ancaman terhadap pesantren di Indonesia.
Riset dari Inter-American Development Bank menekankan bahwa meski ada manfaat pendidikan, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari—seperti waktu untuk festival keagamaan atau interaksi lintas generasi—bisa mengikis identitas kultural.
Di AS, sekolah tradisional yang beralih ke model longer day harus menyesuaikan dengan nilai komunitas, agar tidak “mendehumanisasi” pendidikan seperti yang dikhawatirkan para kritikus.
Dari pengamatan-pengamatan spesifik ini—mulai dari kelelahan siswa di Jakarta hingga konflik dengan madrasah di pedesaan, dan paralel internasional—muncul pola umum: kebijakan sekolah lima hari full day memperkuat model pendidikan yang efisien secara administratif tapi berisiko mematikan aspek holistik.
Ini mengingatkan pada kritik Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, di mana pendidikan “gaya bank” menjadikan siswa sebagai penerima pasif, bukan partisipan aktif dalam dialog pembebasan.
Waktu panjang di sekolah memperburuk ini, mengubah institusi menjadi tempat transfer informasi semata, tanpa ruang untuk interaksi sosial yang membebaskan.
Serupa, Everett Reimer dalam School is Dead menyoroti kegagalan sekolah formal yang terjebak kurikulum kaku, mengabaikan “hidden curriculum” seperti etika dan spiritualitas yang dipelajari di luar kelas—persis seperti hilangnya peran pesantren dalam membangun kebijaksanaan hidup.
Libur dua hari, yang dimaksudkan sebagai keuntungan, justru menjadi ancaman tanpa pengawasan: anak-anak mengisi waktu dengan aktivitas pasif, bahkan cenderung negatif, memperlemah ikatan keluarga dan meningkatkan kerentanan terhadap konsumtivisme digital.
Dari perspektif ekonomi, meski ada potensi peningkatan employability jangka panjang seperti di reformasi 1970-an, biaya implementasi—seperti fasilitas tambahan dan kesejahteraan guru—sering diabaikan, sementara dampak kesehatan mental bisa menimbulkan beban sosial lebih besar.
Pada akhirnya, pengalaman lapangan ini menuntun kita pada kesimpulan sistemik: pendidikan nasional harus kolaboratif, bukan dominan.
Sekolah formal seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, lembaga kultural seperti majelis taklim, TPQ, Madrasah Diniyah atau sanggar-sanggar seni.
Efisiensi waktu bisa dicapai melalui manajemen kelas yang lebih baik, bukan perpanjangan jam, agar tetap menjaga keseimbangan intelektual, moral, spiritual, dan kultural.
Tanpa koreksi, kebijakan ini berisiko melahirkan generasi cerdas tapi miskin kesadaran kritis—sebuah krisis yang melampaui birokrasi, menyentuh inti identitas bangsa.

Oleh : Muhammad Ainur Rifqi. Guru Madrasah Diniyah, Nahdliyyin.