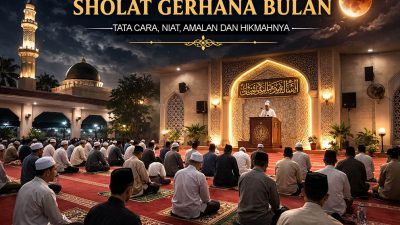Setiap kali kursi Menteri Pendidikan berganti, maka satu hal yang nyaris bisa dipastikan ikut berubah: arah kebijakan pendidikan. Seolah-olah sistem pendidikan kita adalah laboratorium politik, dan para siswa adalah objek eksperimen yang harus siap menerima formula-formula baru setiap lima tahun sekali.
Kebijakan terbaru yang diumumkan pemerintah, menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA (Tempo, 14/4) adalah satu dari sekian banyak perubahan yang mengulang lingkaran lama, bukan membangun arah baru.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai koreksi atas kebijakan sebelumnya. Tapi bagi mereka yang menjalani langsung di ruang-ruang kelas, ini terasa seperti langkah tanpa arah.
Kita pernah menekankan penjurusan, lalu menghapusnya demi “kebebasan minat.” Kini kita kembali lagi ke model lama, seolah tak pernah ada evaluasi yang utuh, hanya putaran balik karena rasa tidak puas yang belum tuntas.
Bukan tidak boleh berubah. Namun jika setiap perubahan tidak didasari oleh riset mendalam, pengalaman lapangan, dan evaluasi jangka panjang, maka yang terjadi hanyalah bongkar pasang yang melelahkan.
Lihat saja beberapa contoh dalam dua dekade terakhir. Dulu kita mengenal Kurikulum 2006 (KTSP) yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan muatan lokal.
Belum selesai membenahi, datang Kurikulum 2013 yang mengusung pendidikan karakter dan integrasi lintas mata pelajaran. Namun dalam pelaksanaannya, guru kelimpungan, pelatihan terburu-buru, dan buku ajar tidak seragam.
Ketika publik mulai menyesuaikan, datang gagasan baru bernama Kurikulum Merdeka yang justru membongkar struktur lama dan menekankan fleksibilitas tanpa arah yang solid. Di satu sisi, guru dituntut berinovasi; di sisi lain, sistem evaluasi masih kaku dan seragam.
Perubahan demi perubahan ini tidak memberi ruang cukup bagi sekolah untuk benar-benar matang menjalankannya.
Contoh lainnya adalah soal Ujian Nasional. Setelah bertahun-tahun menjadi penentu kelulusan, tiba-tiba dihapus. Dalihnya bagus: menghapus stres siswa dan memberi ruang penilaian yang lebih menyeluruh.
Tapi penghapusan itu tidak disertai sistem pengganti yang memadai. Asesmen Nasional diperkenalkan, namun masih belum semua pihak paham substansi dan tujuannya. Banyak guru bahkan mengaku belum siap, tetapi kebijakan jalan terus karena memang sudah harus jalan.
Anak-anak kita butuh konsistensi. Mereka butuh waktu dan ruang untuk mengenali diri, mengembangkan potensi, serta menemukan panggilan hidupnya. Tapi ketika arah pendidikan berganti setiap periode kekuasaan, pijakan mereka menjadi rapuh.
Hari ini mereka diminta belajar lintas minat. Besok dipaksa memilih jalur spesifik karena dinilai lebih efisien. Lusa, bisa jadi berubah lagi karena visi menteri yang baru. Di mana sebenarnya posisi anak dalam kebijakan pendidikan? Sebagai subjek atau objek?
Guru pun mengalami nasib serupa. Mereka yang seharusnya menjadi ujung tombak pendidikan sering kali menjadi korban kebijakan dadakan. Kurikulum berganti, pelatihan minim, perangkat ajar tidak seragam, dan tuntutan administrasi justru makin kompleks.
Mereka harus mengikuti arahan baru sebelum selesai memahami yang lama. Guru menjadi operator perubahan, bukan pemilik proses pembelajaran. Ini menyakitkan, sebab kualitas pendidikan sesungguhnya hanya bisa dibangun lewat pendidik yang tenang dan diberi ruang tumbuh.
Lalu kita bertanya, apakah negara-negara lain juga mengalami hal serupa? Tidak. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang matang seperti Finlandia, Korea Selatan, atau Singapura membangun kebijakannya dengan satu prinsip utama: kesinambungan.
Di Finlandia, sistem pendidikan dibangun berdasarkan filosofi sosial dan kepercayaan tinggi pada guru, bukan sekadar inovasi kurikuler. Di Korea Selatan, meski tekanan akademik tinggi, arah pendidikannya jelas dan terukur, bukan hasil tarik ulur antara ego kekuasaan dan tuntutan politis.
Singapura menempatkan riset sebagai landasan utama kebijakan pendidikan, bukan sekadar visi personal seorang pejabat. Di sana, pendidikan adalah proyek kebangsaan, bukan program menteri.
Kita membutuhkan keberanian untuk mengatakan cukup terhadap siklus kebijakan tambal sulam. Pendidikan bukan ruang pamer gagasan baru tiap periode. Ia adalah proses membentuk manusia seutuhnya, yang tak bisa digarap dalam logika politis jangka pendek.
Sudah saatnya kita memiliki grand design pendidikan nasional yang kokoh, teruji, dan mengikat secara lintas periode. Kebijakan tidak boleh lahir dari obsesi pencitraan, tapi dari dialog panjang dengan realitas dan kebutuhan masa depan.
Anak-anak kita bukan kelinci percobaan. Mereka bukan variabel yang bisa diubah sesuka waktu. Mereka adalah masa depan bangsa yang tak boleh dibentuk dengan kebijakan coba-coba.
Jika kita ingin membangun Indonesia yang benar-benar maju, mulailah dari pendidikan yang konsisten, jernih, dan berpihak pada keberlangsungan, bukan semata gebrakan.
Muhammad Ainur Rifqi
PCNU Jombang