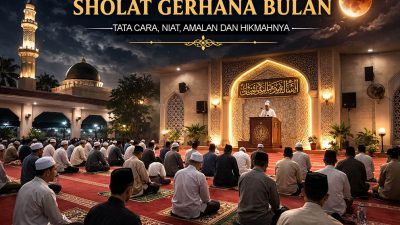Jombang, pcnujombang.or.id – Era post-truth adalah zaman ketika narasi mengalahkan nalar, emosi mengalahkan verifikasi, dan viralitas sering menjadi sebuah kebenaran. Dalam konteks ini, kepemimpinan Nahdlatul Ulama memiliki tantangan yang berat, bukan sekadar mengelola organisasi, namun juga bagaimana menjaga kesadaran dan kewarasan jamaah di tengah banjir informasi yang simpang siur.
Di titik inilah Napak Tilas NU menjadi relevan. Napak tilas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kompas etik untuk menilai apakah kepemimpinan NU hari ini masih berjalan di jejak para muassis dan masyayikh, atau justru terseret arus kegaduhan post-truth yang reaktif.
Napak Tilas sebagai Isyarah Pendirian NU
Dalam tradisi pesantren, napak tilas merupakan isyarah. Ia menandai bahwa NU lahir dari sanad keilmuan, laku batin, dan kesadaran sejarah, bukan dari kepentingan sesaat. Jejak perjalanan para pendiri NU—dari Bangkalan hingga Tebuireng—menegaskan bahwa NU berdiri di atas kesinambungan sanad. Syaikhona Kholil Bangkalan memberi isyarah, KH Hasyim Asy’ari menerjemahkannya dalam bentuk jam’iyyah, dan NU tumbuh sebagai rumah besar umat.
Puncak Napak Tilas NU ditandai dengan penyerahan simbol historis berupa tongkat dan tasbih. KH Fachruyddin Aschol, cicit Syaikhona Kholil, menyerahkan simbol tersebut kepada KH Azaim Ibrohimi, cucu Kiai As’ad Samsul Arifin dan Pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo. Selanjutnya, KH Azaim Ibrohimi membawa simbol tongkat dan tasbih ke Tebuireng untuk menyerahkannya kepada KH Fahmi Amrullah Hadziq (Gus Fahmi), cucu Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari.
Dalam tradisi NU, tongkat melambangkan keteguhan kepemimpinan, sementara tasbih melambangkan kedalaman spiritualitas. Keduanya menjadi pesan kuat bahwa kepemimpinan NU harus berjalan seimbang antara otoritas dan dzikir, ketegasan dan kebijaksanaan. Kepemimpinan tanpa spiritualitas akan kering, sementara spiritualitas tanpa tanggung jawab sosial akan kehilangan relevansinya.
Napak Tilas: Simbol Kepemimpinan Berbasis Laku, Bukan Narasi
Napak tilas juga mengajarkan bahwa kepemimpinan NU bertumpu pada laku, bukan narasi. Para muassis membesarkan NU melalui keteladanan dan kesabaran, bukan penguasaan opini. Filsafat Jawa menyebutnya sepi ing pamrih, rame ing gawe—prinsip yang justru kontras dengan watak post-truth yang gaduh dan instan.
Dalam hadis, dari hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw bersabda :
كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
“Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar.”
(HR. Muslim No. 5)
Hadits ini adalah peringatan keras bagi kepemimpinan di era sekarang bahwa tidak semua yang ramai dan viral itu benar. Maka penting bagi kita sebagai warga Nahdliyin untuk tidak mudah menceritakan apapun yang kita dengar yang belum tentu kebenarannya. Ini menjadi peringatan keras agar kita selektif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan berita.
Karena itu, kepemimpinan NU di era post-truth dituntut menjernihkan, bukan memenangkan narasi. Klarifikasi yang emosional kerap lebih merusak daripada diam yang bijak. Pembelaan yang reaktif sering kali justru memperlebar konflik dan menggerus kepercayaan jamaah.
Napak Tilas NU pada akhirnya menegaskan satu pesan penting: NU besar karena adab, kuat karena kesabaran, dan hidup karena kepercayaan umat. Selama kepemimpinan NU hari ini setia pada jejak para masyayikh—menjaga adab, menimbang maslahat, dan menahan ego—NU akan tetap menjadi penunjuk arah moral, bahkan di tengah riuh dan kabut post-truth.