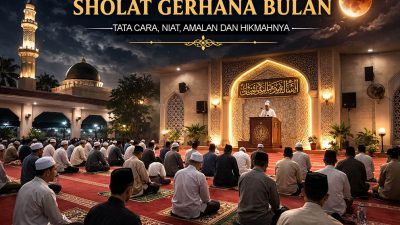Lebih jauh, refleksi ini juga menimbang kembali apakah kebijakan enam hari belajar yang lebih lama kita terapkan sebelumnya justru lebih relevan, proporsional, dan sejalan dengan kebutuhan anak.
Kebijakan pendidikan selalu menjadi faktor strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa, sebab menyangkut langsung pada generasi penerus. Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang lima hari belajar. Namun, kebijakan ini kemudian tidak berlaku lagi setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
Harapan awalnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi anak untuk beraktivitas di luar sekolah, termasuk dalam keluarga dan masyarakat. Akan tetapi, perjalanan kebijakan tersebut justru menyisakan banyak catatan kritis, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas terhadap tumbuh kembang anak.
Dengan melihat secara menyeluruh bagaimana anak-anak mengalami proses belajar, tumbuh, dan berkembang, kita dapat menilai apakah sistem lima hari belajar sepekan benar-benar memberikan manfaat atau justru menimbulkan dampak yang kurang mendukung perkembangan mereka.
Lebih jauh, refleksi ini juga menimbang kembali apakah kebijakan enam hari belajar yang lebih lama kita terapkan sebelumnya justru lebih relevan, proporsional, dan sejalan dengan kebutuhan anak.
Anak adalah pribadi yang tengah tumbuh dengan ritme alamiah. Masa kanak-kanak, baik di usia dini maupun jenjang pendidikan dasar dan menengah, merupakan periode emas yang menentukan arah perkembangan kepribadian, kemampuan kognitif, emosi, sosial, dan moral.
Dalam konteks inilah, setiap kebijakan pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan dasar anak. Kebijakan lima hari belajar yang sejak awal diharapkan menjadi solusi praktis ternyata menyisakan problem karena tidak sejalan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kapasitas anak dalam menerima beban belajar yang panjang setiap harinya. Ketika sekolah dipadatkan hanya dalam lima hari, otomatis jam belajar dalam sehari menjadi lebih panjang. Anak-anak, terutama di tingkat dasar, sering kali mengalami kelelahan karena harus duduk, menyimak, dan mengerjakan berbagai aktivitas akademis dalam waktu yang melebihi kemampuan fokus mereka.
Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Brain Balance Center, disebutkan kalau rentang konsentrasi anak yang ideal adalah dua hingga tiga menit dikali usia mereka. Rentang atensi sekitar 2–3 menit per tahun usia, yang juga menghasilkan estimasi serupa, yakni 20–30 menit untuk anak usia sepuluh tahun.
Sementara itu, pola belajar yang dipadatkan membuat anak terpaksa menghabiskan waktu lebih lama di kelas meskipun tingkat penerimaan materi sudah menurun. Akibatnya, efektivitas belajar justru berkurang.
Lebih jauh, beban waktu panjang ini berimplikasi pada aspek sosial dan emosional anak. Banyak anak pulang dalam kondisi lelah, sehingga waktu yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan keluarga, bermain dengan teman sebaya, atau mengembangkan minat non-akademis justru habis untuk beristirahat. Interaksi keluarga yang seharusnya menjadi inti penguatan pendidikan karakter tidak tercapai karena anak-anak lebih banyak tertidur lebih awal atau tidak lagi memiliki energi untuk berbicara panjang dengan orang tuanya.
Kondisi semacam ini pada akhirnya mereduksi tujuan awal kebijakan lima hari belajar itu sendiri. Alih-alih memperkuat pendidikan karakter melalui interaksi di luar sekolah, anak-anak justru kehilangan kesempatan berharga tersebut. Mereka menjadi bagian dari generasi yang waktunya lebih tersita di sekolah, tetapi dengan kualitas keterlibatan yang menurun.
Di sisi lain, pendekatan lima hari belajar ini tidak memperhatikan kebutuhan perkembangan motorik anak. Dalam sistem lama enam hari belajar, anak masih memiliki jeda harian yang lebih seimbang. Kegiatan belajar yang dibagi lebih merata membuat beban harian anak lebih ringan. Mereka masih bisa mengikuti kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, atau aktivitas sosial tanpa harus berbenturan dengan rasa lelah berlebihan.
Dalam lima hari belajar, aktivitas non-akademis tersebut kerap tersisih karena sekolah sudah terlalu lama menyita waktu. Padahal, tumbuh kembang anak memerlukan keseimbangan antara stimulasi kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada kualitas perkembangan generasi.
Refleksi juga perlu dilakukan dengan mengaitkan kebijakan lima hari belajar dengan Catur Pusat Pendidikan. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan anak berlangsung dalam empat pusat utama, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Dalam praktiknya, kebijakan lima hari belajar cenderung memusatkan aktivitas pendidikan hanya pada ranah sekolah, dengan mengorbankan peran tiga pusat lainnya.
Keluarga sebagai pusat pendidikan pertama justru kehilangan ruang karena anak terlalu lelah untuk membangun komunikasi yang intensif dengan orang tua. Waktu kebersamaan yang mestinya digunakan untuk menanamkan nilai, bercerita, atau sekadar membangun ikatan emosional menjadi terbatas.
Masyarakat sebagai pusat pendidikan juga tidak mendapat tempat karena waktu luang anak habis untuk istirahat. Kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, atau budaya yang biasanya memberi warna pendidikan karakter tidak lagi terjangkau. Bahkan diri anak itu sendiri, sebagai pusat pendidikan yang memungkinkan mereka mengeksplorasi minat, bakat, dan refleksi personal, tidak mendapatkan porsi karena mereka terjebak dalam rutinitas yang terlalu padat.
Hal ini berbanding terbalik dengan sistem enam hari belajar yang lebih proporsional. Dengan beban harian lebih ringan, anak masih memiliki energi untuk hidup dalam keseimbangan keempat pusat pendidikan tersebut. Mereka bisa belajar di sekolah, berinteraksi sehat dengan keluarga, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Inilah wujud pendidikan yang lebih menyeluruh, tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga tumbuh kembang anak secara utuh.
Dampak jangka panjang dari pemaksaan lima hari belajar terhadap tumbuh kembang anak tidak bisa dipandang remeh. Anak yang tumbuh dalam tekanan waktu panjang cenderung lebih rentan mengalami stres, kehilangan motivasi belajar, dan menunjukkan gejala kejenuhan lebih dini.
Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Syamsu Yusuf LN.) menjelaskan bahwa tekanan berlebihan dalam proses belajar dapat menimbulkan stres pada anak serta mempengaruhi motivasi dan kesehatan emosionalnya. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi pengalaman yang membahagiakan, yang memberi ruang bagi anak untuk menemukan makna, bukan sekadar beban yang harus dijalani.
Refleksi kritis ini menuntun kita pada sebuah kesimpulan penting bahwa kebijakan lima hari belajar, meskipun lahir dari niat baik, tidak sejalan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak Indonesia. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru. Jika tujuan utama adalah memperkuat pendidikan karakter dan kualitas pembelajaran, maka langkah yang lebih tepat adalah kembali kepada enam hari belajar dengan distribusi beban yang lebih proporsional.
Enam hari belajar bukan berarti menambah tekanan pada anak, tetapi justru membagi beban dengan lebih seimbang. Dengan waktu yang lebih merata, anak-anak tidak harus mengorbankan kebutuhan sosial, emosional, dan fisik mereka. Pendidikan karakter pun bisa lebih mudah diwujudkan karena ruang keluarga, masyarakat, dan diri anak sendiri tetap memiliki tempat dalam proses pendidikan.
Dalam kerangka Catur Pusat Pendidikan, sistem enam hari memberi keseimbangan peran bagi keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pusat, melainkan bagian dari ekosistem yang saling melengkapi. Anak-anak pun dapat tumbuh lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih bahagia. Pendidikan kemudian benar-benar menjadi alat pembentukan generasi, bukan sekadar rutinitas belajar yang memenjarakan mereka dalam jadwal yang padat.
Melalui refleksi ini, kita diajak kembali pada semangat awal pendidikan nasional, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat.
Semangat tersebut jelas tidak dapat diwujudkan dengan memaksakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Sudah saatnya kita mengevaluasi kembali pelaksanaan lima hari belajar dan dengan jujur mengakui bahwa kebijakan enam hari belajar lebih sesuai dengan konteks tumbuh kembang anak Indonesia.
Kembali ke enam hari belajar bukan berarti mundur dari modernisasi pendidikan. Justru sebaliknya, ini adalah upaya menempatkan kebijakan pada jalur yang tepat, yang berpihak pada anak sebagai subjek utama pendidikan.
Dengan distribusi waktu yang lebih proporsional, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar mendukung anak untuk tumbuh seutuhnya, tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam karakter, kesehatan, dan kebahagiaan.

Penulis : Astatik
Pengembang Budaya Edukatif, Pendiri PKBM Bestari Jombang, dan Praktisi Pendidikan Formal, Non-formal dan Informal