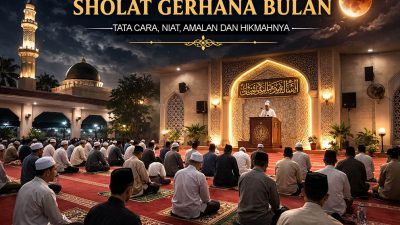Hari ini, 2 Mei, kembali kita berdiri dalam seremoni rutin: memperingati Hari Pendidikan Nasional. Layar-layar media sosial akan penuh dengan kutipan bijak Ki Hadjar Dewantara, ucapan terima kasih kepada guru-guru, hingga parade foto-foto perayaan dari sekolah-sekolah di seluruh negeri.
Satu pertanyaan sederhana namun menusuk hati kemudian muncul: apakah pendidikan kita hari ini telah sejalan dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa?
Sejarah mencatat, para pendiri bangsa kita menempatkan pendidikan bukan sekadar sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi sebagai jalan menuju kemerdekaan sejati: bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan mental, dan bebas untuk merdeka berpikir.
Ki Hadjar Dewantara tegas menyatakan, pendidikan harus menjadi ruang untuk “menghidupkan” manusia, bukan “menyeragamkan” apalagi “mematikan” kreativitasnya.
Namun, melihat pendidikan kita hari ini, rasa-rasanya kita masih jauh dari cita-cita tersebut. Kita masih terpaku pada angka-angka, nilai rapor, dan capaian akademis yang terlalu kaku.
Para guru kita, meski bergelar “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa,” masih terjebak dalam birokrasi pendidikan yang lebih menghargai dokumen administrasi daripada inovasi di kelas. Kesejahteraan guru pun, kenyataannya, sering menjadi ironi pahit yang nyaris selalu kita abaikan.
Laporan terbaru dari media nasional (Kompas, 2/5) pada Hari Pendidikan Nasional ini menggarisbawahi betapa guru kini makin lelah menghadapi perubahan kebijakan yang terus-menerus.
Mereka harus beradaptasi dengan kurikulum yang berganti tiap periode, metode pengajaran yang berubah-ubah, serta tumpukan administrasi kepegawaian yang makin memberatkan.
Guru bukan hanya dituntut untuk mendidik, tapi juga menjadi operator sistem digital yang kadang belum siap dijalankan secara merata.
Rosyidin, salah seorang guru Madrasah di Gresik yang juga kawan saya, pernah bercerita bahwa dirinya sudah mengajar selama lebih dari dua dekade dan belum pernah merasakan beban sekompleks sekarang.
Ia harus memutar tenaga untuk menyusun laporan administrasi, menghadiri pelatihan, mengejar target Kurikulum Merdeka, sambil tetap mengajar dan mengurusi kebutuhan anak-anak muridnya.
Semangat untuk mengabdi tetap ada, tapi energi dan waktu terkuras oleh sistem yang terus berubah. “Saya melihat setiap perubahan sebagai harapan untuk lebih baik, tapi pemerintah sepertinya tak pernah melihat kondisi riil para guru”, ujarnya lirih.
Jika kita melihat lebih luas, ada satu masalah mendasar dalam dunia pendidikan kita: inkonsistensi dan kurangnya keberlanjutan kebijakan.
Setiap pergantian menteri, seolah ada pergantian paradigma. Padahal, pendidikan bukan arena uji coba kebijakan jangka pendek.
Ia adalah proyek peradaban, yang menuntut konsistensi arah, dukungan sumber daya, dan evaluasi yang serius—bukan hanya ganti istilah dan program setiap lima tahun.
Alih-alih memperbaiki akar persoalan, seringkali energi habis untuk mengejar program-program kosmetik yang tidak menyentuh akar ketimpangan.
Misalnya, digitalisasi pendidikan dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah pelosok, tanpa mempertimbangkan ketersediaan listrik, sinyal internet, dan kemampuan dasar guru dalam menggunakan teknologi. Akhirnya, program ini menjadi beban tambahan, bukan solusi.
Kesejahteraan guru juga menjadi persoalan besar yang terlalu lama diabaikan. Masih banyak guru honorer yang digaji tidak manusiawi.
Belum lagi persoalan rekrutmen ASN yang tidak merata, atau program peningkatan kompetensi yang tidak merata. Di saat yang sama, tuntutan kepada guru terus meningkat: harus kreatif, adaptif, inovatif, sabar, dan berintegritas. Seringkali, itu semua dituntut tanpa didukung oleh sistem yang adil dan memadai.
Maka, Hari Pendidikan Nasional bukan hanya hari untuk mengenang jasa para guru dan tokoh pendidikan. Ia harus menjadi hari perenungan nasional: apa yang telah kita lakukan untuk benar-benar memanusiakan pendidikan?
Sudahkah sistem pendidikan kita memerdekakan guru dari tekanan administratif, membebaskan siswa dari penyeragaman, dan menyemai semangat belajar yang tulus dan kritis?
Sudah waktunya kita keluar dari budaya seremoni tanpa aksi. Pendidikan bukan soal upacara, tapi keberpihakan. Bukan soal jargon, tapi keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada guru dan murid.
Jika tidak, kita hanya akan terus memperingati Hari Pendidikan dengan pujian yang hampa—sementara kualitas pendidikan kita tetap terperosok dalam realitas yang menyedihkan.
Refleksi jujur ini penting, bukan untuk menambah keputusasaan, tapi agar kita bisa melihat lebih jelas dan memperbaiki apa yang harus kita benahi.
Karena, hanya dengan menyadari kekurangan-kekurangan itu, kita bisa mengembalikan pendidikan pada esensinya yang sejati: memerdekakan manusia Indonesia.