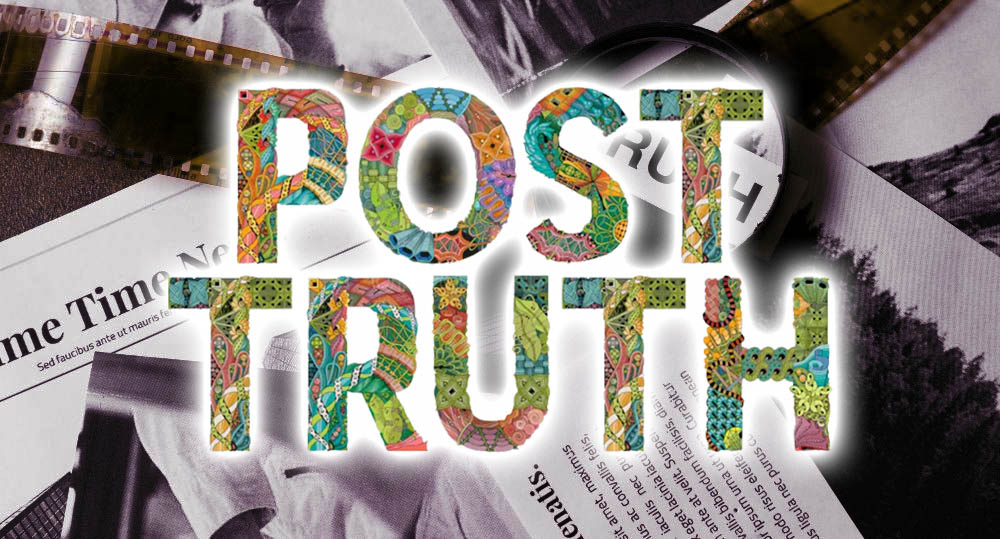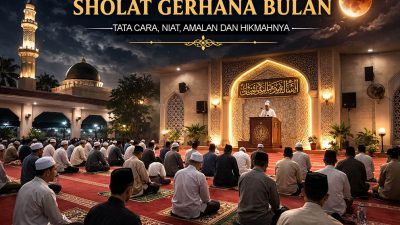Fenomena Baru: Dari Budaya Klarifikasi ke Budaya Pembatalan
Jombang, pcnujombang.or.id – Dulu, perbedaan pendapat sebuah kewajaran. Orang bisa berdiskusi, bahkan berdebat, tanpa kehilangan rasa hormat. Kini, di era digital, hal itu mulai memudar. Muncul fenomena baru cancel culture — budaya “membatalkan” seseorang hanya karena pandangan, ucapan, atau tindakan yang salah dan berbeda.
Satu kesalahan kecil di media sosial bisa menjadi badai besar. Satu potongan video bisa menjatuhkan reputasi seseorang seketika. Dan dalam hitungan jam, publik berubah menjadi hakim: menghukum tanpa proses, memvonis tanpa tabayyun.
Di media sosial, kebenaran bukan lagi hasil dialog rasional, melainkan hasil pertarungan emosi. Jurgen Habermas (1989) menyebut kondisi ini sebagai hilangnya rational communicative action — tindakan komunikasi rasional — di mana ruang publik gagal menjadi tempat diskusi, dan berubah menjadi arena saling serang.
Post-Truth Society: Ketika Emosi Lebih Kuat dari Kebenaran
Saat ini, Kita sedang berada di era Post-Truth — Istilah yang diperkenalkan oleh Lee McIntyre (2018) dalam bukunya Post-Truth. Ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat ini, emosi dan opini pribadi lebih mempengaruhi pandangan publik daripada fakta objektif.
Masyarakat Post-Truth lebih cepat marah daripada memahami. Orang mudah percaya pada berita yang “terasa benar” walau tanpa bukti, dan menolak fakta yang tidak sesuai dengan perasaannya.
Fenomena cancel culture lahir dari atmosfer semacam itu, orang tidak lagi peduli apakah sesuatu benar atau salah. Namun, siapa yang mengatakannya — dan seberapa besar perasaan mereka tersinggung.
Ketika Moralitas Menjadi Ajang Kompetisi
Ironinya, cancel culture sering muncul atas nama moralitas: ingin melawan ketidakadilan, menegur kesalahan, atau memperjuangkan kebenaran. Namun dalam praktiknya, moral berubah menjadi senjata sosial.
Fenomena ini sejalan dengan analisis Michel Foucault tentang “politik kebenaran” (politics of truth) — bahwa di setiap masyarakat, selalu ada kekuasaan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Siapa yang paling lantang mengkritik, ialah yang paling benar. Siapa yang salah sekali, langsung kehilangan hak klarifikasi dan berbicara. Budaya ini justru bertentangan dengan semangat Islam yang mengajarkan kasih sayang, tabayyun, dan perbaikan.
Padahal Islam mengajarkan jalan yang lebih mulia. Allah berfirman:
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
“Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Balaslah dengan cara yang lebih baik.” (QS. Fushshilat: 34)
Ayat ini menegaskan bahwa Islam menuntun kita untuk menegur dengan cara yang lembut, bukan menghancurkan martabat seseorang.
Gusdur dan Spirit Kemanusiaan
Warga Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab moral untuk melawan budaya pembatalan dengan budaya kasih sayang (culture of compassion). Gus Dur pernah berpesan :
“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”
Spirit inilah yang seharusnya menjadi panduan kita di ruang digital. Mengoreksi boleh, mengingatkan perlu, tetapi menjatuhkan bukanlah jalan yang benar. Para Ulama selalu mengajarkan kita untuk mengajak, bukan mengusir; menuntun, bukan menghakimi.
Masyarakat post-truth tidak akan berubah jika kita terus hidup dari emosi ke emosi. Maka, budaya ini bisa terselamatkan hanya dengan kesadaran spiritual — bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan, bukan pembatalan.
Mari menjadikan ruang maya sebagai ladang dakwah kebaikan. Karena di tengah budaya membatalkan, justru memaafkan adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya.