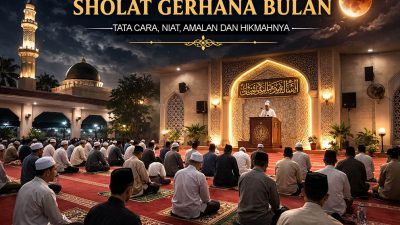Gelar Pahlawan di Zaman Paradoks
Jombang, pcnujombang.or.id – Hari Pahlawan menjadi momentum untuk refleksi dan mengenang jasa para pahlawan. Di masa lalu, para pahlawan berani menantang maut demi kebenaran. Namun kini, banyak orang justru berebut gelar “pahlawan” dengan cara yang berbeda—bukan dengan pengorbanan, melainkan dengan rekayasa citra.
Saat ini, kita hidup di zaman paradoks: banyak yang mengaku berjasa, padahal jasanya lahir dari panggung pencitraan, bukan dari nurani dan perjuangan tulus. Bahkan, berbagai kemunafikan yang tampak, seakan-akan bukan menjadi halangan untuk mendapatkan gelar “Pahlawan”
Pahlawan Rekayasa di Era Kamera
Kita melihat munculnya generasi pahlawan digital—mereka berjuang bukan di medan perang, tapi di depan kamera. Mereka sibuk mendokumentasikan setiap gerakan seolah semua harus tampak heroik. Tanpa sorotan kamera, perjuangan mereka terasa hampa.
Padahal, pahlawan sejati tidak membutuhkan sorotan. Mereka bekerja dalam diam, menebar manfaat tanpa gembar-gembor, dan meninggalkan jejak keikhlasan, bukan jejak algoritma. Sementara itu, “pahlawan rekayasa” menciptakan cerita kepahlawanan yang indah di layar, tapi kosong di hati.
Kaidah fiqhiyyah “Al-umur bi maqashidiha” — segala perkara bergantung pada niatnya — mengingatkan kita bahwa nilai perjuangan terletak pada niat, bukan pada tampilan. Karena itu, “pahlawan rekayasa” sejatinya bukan pahlawan, tetapi pelaku pencitraan yang menipu publik dan dirinya sendiri.
Ketika Jasa Diciptakan, Bukan Diperjuangkan
Krisis ini muncul ketika makna jasa berubah dari pengabdian menjadi pencitraan. Banyak orang lebih sibuk mengatur panggung perjuangan daripada benar-benar berjuang. Mereka merancang program bukan karena rakyat membutuhkan, tetapi karena popularitas menggiurkan.
Mereka menulis pernyataan dengan bantuan tim media, menyusun skenario aksi, lalu mengunggah hasilnya dengan gaya sinematik. Dunia maya akhirnya menjadi panggung bagi pahlawan palsu—pahlawan yang tampak berjasa di linimasa, tapi tak berbekas di dunia nyata.
Rekayasa Kepahlawanan, Rekayasa Kebenaran
Krisis ini tidak hanya menggerus keikhlasan, tapi juga merusak moral publik. Masyarakat yang terbiasa mengagumi kepalsuan akan kehilangan rasa pada keaslian. Kita lebih mudah percaya pada pencitraan daripada pengorbanan.
Bahkan sejarah bisa mereka ubah. Orang yang berkuasa bisa menulis dirinya sebagai pahlawan, padahal dia pelaku kezaliman. Sementara pejuang sejati yang bekerja tanpa panggung terlupakan begitu saja.
Kaidah fiqhiyyah “Mā bunia ‘ala al-bāthil fa huwa bāthil” — segala yang dibangun di atas kebatilan, hasilnya juga batil — menegaskan bahwa kepahlawanan yang lahir dari kebohongan tidak memiliki nilai. Keberhasilan yang dibangun dengan manipulasi tidak akan membawa keberkahan, justru menjerumuskan pelakunya pada kesombongan dan kehancuran.
Menemukan Lagi Kejujuran dalam Kepahlawanan
Menjadi pahlawan bukan soal siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang paling jujur. Kejujuran menjadi inti perjuangan. Tanpa kejujuran, jasa hanya berubah menjadi sandiwara. Kepahlawanan sejati lahir dari hati yang berani menghadapi kenyataan, bukan dari tangan yang pandai mengatur pencitraan.
Kaidah fiqhiyyah “Al-jazā’ min jinsil ‘amal” — balasan sepadan dengan perbuatan — mengingatkan bahwa ketulusan melahirkan keberkahan, sedangkan kepalsuan berujung kehinaan. Pahlawan jujur mungkin tidak terkenal, tetapi amalnya abadi. Sementara pahlawan rekayasa bisa viral hari ini, lalu lenyap esok hari.
Pahlawan Sejati, Tidak Butuh Pengakuan
Krisis pahlawan bukan berarti tidak ada yang berjuang, tetapi terlalu banyak yang berpura-pura berjuang. Mereka menulis naskah kepahlawanan untuk diri sendiri dan memainkan peran yang mereka ciptakan. Dunia menjadi panggung besar, dan kebenaran berubah menjadi naskah yang dipelintir.
Namun sejarah sejati tidak bisa mereka tipu. Waktu akan memisahkan antara jasa yang tulus dan jasa yang direkayasa. Pahlawan sejati tidak mencari pengakuan—karena cukup Tuhan yang tahu siapa yang benar-benar berjuang.